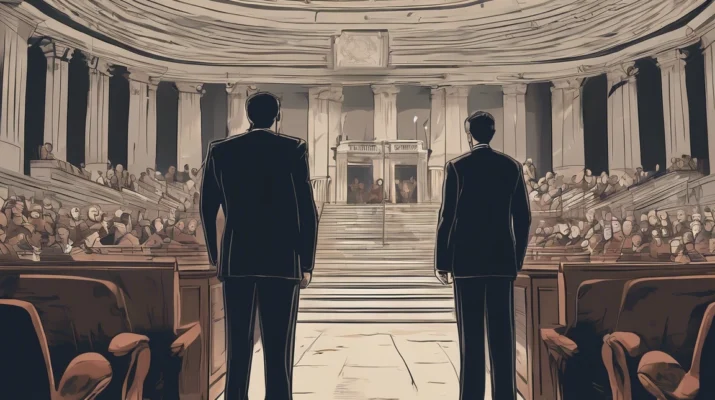Sholeh UG
Keberanian bukanlah soal absennya rasa takut. Ia bukan milik orang-orang yang tak pernah gemetar hatinya, bukan milik mereka yang tak pernah dibayangi kekhawatiran. Justru, keberanian adalah keputusan untuk tetap melangkah ketika tubuh diguncang gemetar, ketika pikiran penuh tanda tanya, dan ketika rasa takut berdiri tepat di hadapan kita. Keberanian bukanlah kemenangan atas rasa takut, tapi keputusan untuk tidak tunduk padanya.
Baca juga: Negeri Miskin Imajinasi: Kekuasaan Tanpa Cahaya
Mari kita mundur sejenak, melihat kembali pada tahun politik 2024. Tahun yang dicatat sejarah bukan hanya sebagai kontestasi kekuasaan, tapi juga ujian moral dan keberanian bangsa. Saat itu, kekuasaan tumbuh dengan wajah hegemonik. Tak hanya menguasai ruang politik, tetapi juga mengintervensi ruang hukum yang seharusnya netral dan adil. Mahkamah Konstitusi — benteng terakhir penjaga konstitusi — justru menjadi catatan luka. Ketika syarat usia untuk pencalonan diubah demi melanggengkan kekuasaan tertentu, publik sadar: keberanian telah dikalahkan oleh kepentingan.
Suara Perubahan
Namun, di tengah atmosfer yang menyesakkan itu, muncul suara yang melawan. Suara tentang perubahan. Apakah mereka tak takut? Tentu takut. Mereka tahu risikonya: difitnah, diserang, dicari-cari kesalahan, bahkan diteror. Tapi mereka tetap berjalan. Ketakutan tidak mereka hilangkan, melainkan mereka kalahkan. Bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan keyakinan yang bersumber dari dalam diri—bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka mungkin kalah dalam angka, dalam keputusan Mahkamah, dalam permainan kuasa. Tapi mereka telah menang atas diri mereka sendiri—dan kemenangan itu jauh lebih jujur, lebih langgeng.
Baca juga: Ironi Negeri Demokrasi: Ketika Oposisi Terancam Bui
Dalam momen seperti itu, kita diajak untuk bercermin. Kita semua memiliki pilihan. Diam atau jujur. Menyuarakan kebenaran atau ikut mengalir bersama arus. Pilihan itu tak selalu mudah, bahkan sering menyakitkan. Tapi justru dari pilihan itulah kita mengenal siapa diri kita sesungguhnya.
Kita tumbuh bukan dari keberhasilan demi keberhasilan, tetapi dari luka dan kegagalan. Kebenaran sering kali baru terasa maknanya justru setelah kita jatuh, setelah kita kalah. Sebab dari kekalahan itulah, kita belajar menata ulang kompas nurani kita, kita belajar menolak tunduk meski ditundukkan.
Kemudian, kita mendengar nama Tom Lembong. Ia ditahan atas tuduhan korupsi. Apakah ia tak takut? Tentu takut. Ia tahu tekanan bisa datang dari mana saja. Tapi lihatlah wajahnya dalam persidangan. Tidak ada tanda kepanikan, tidak ada ketergesaan membela diri dengan kemarahan atau kepalsuan. Ia berdiri tegak, jernih, dengan keyakinan yang bersumber bukan dari kekuasaan, melainkan dari nurani. Dan tim kuasa hukumnya, mereka bukan hanya menyampaikan pembelaan hukum—mereka menyuarakan suara hati publik. Mereka menyanyikan pasal-pasal undang-undang dengan irama kejujuran. Sebuah nyanyian nurani yang menggetarkan.

Vox Populi Vox Dei
Suara itu menembus dinding ruang sidang, melampaui meja-meja hakim, dan menyusup ke hati rakyat. Ia tak berteriak, tapi menggema. Ia tidak gaduh, tapi beresonansi. Dan gema itu didengar. Tidak oleh mereka yang tuli terhadap nurani, tapi oleh mereka yang dalam satu titik kesadarannya masih menyisakan ruang bagi suara langit.
Kemudian datanglah sebuah keputusan yang tak terduga: presiden meminta persetujuan DPR untuk memberikan abolisi. Ini bukan sekadar keputusan politik. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa suara rakyat—suara yang lahir dari rasa perih, keadilan yang diinginkan, dan kebenaran yang dituntut—telah sampai ke telinga kuasa. Bukan karena kuasa mendengarnya langsung, tetapi karena semesta memilih menyampaikan suara itu dengan caranya sendiri.
Di sinilah kita kembali menyadari makna sejati dari pepatah lama: Vox Populi, Vox Dei — suara rakyat adalah suara Tuhan. Bukan karena rakyat selalu benar, tapi karena rakyat memiliki nurani. Dan ketika nurani kolektif itu bersuara, semesta merespons. Tuhan tidak hadir dalam wujud petir atau azab, tetapi dalam bentuk tangan-tangan kekuasaan yang—untuk sesaat—dipinjam oleh kebenaran.
Kemenangan Dalam Jiwa
Bahwa keberanian itu bisa dilatih. Ia lahir dari kegagalan, dari tekanan, dari rasa takut yang tidak kita sembunyikan, tetapi kita pelajari dan kita lewati. Keberanian bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang tetap tegak ketika semua hal tampak seolah akan runtuh. Dan ketika keberanian itu muncul dari tempat terdalam diri kita, ia bukan hanya menjadi kekuatan pribadi, tapi cahaya bagi banyak orang.
Mereka yang dulu bersuara tentang perubahan mungkin kalah di atas kertas. Tapi mereka menang di dalam jiwa. Mereka menaklukkan ketakutan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan keyakinan. Dan dari situlah, bangsa ini belajar. Bahwa keberanian bukanlah milik mereka yang kuat, tapi milik mereka yang tetap melangkah meski takut, tetap berkata meski gemetar, tetap berdiri meski sendirian. Karena keberanian sejati, pada akhirnya, adalah bentuk paling murni dari cinta: cinta pada kebenaran, keadilan, dan sesama manusia.